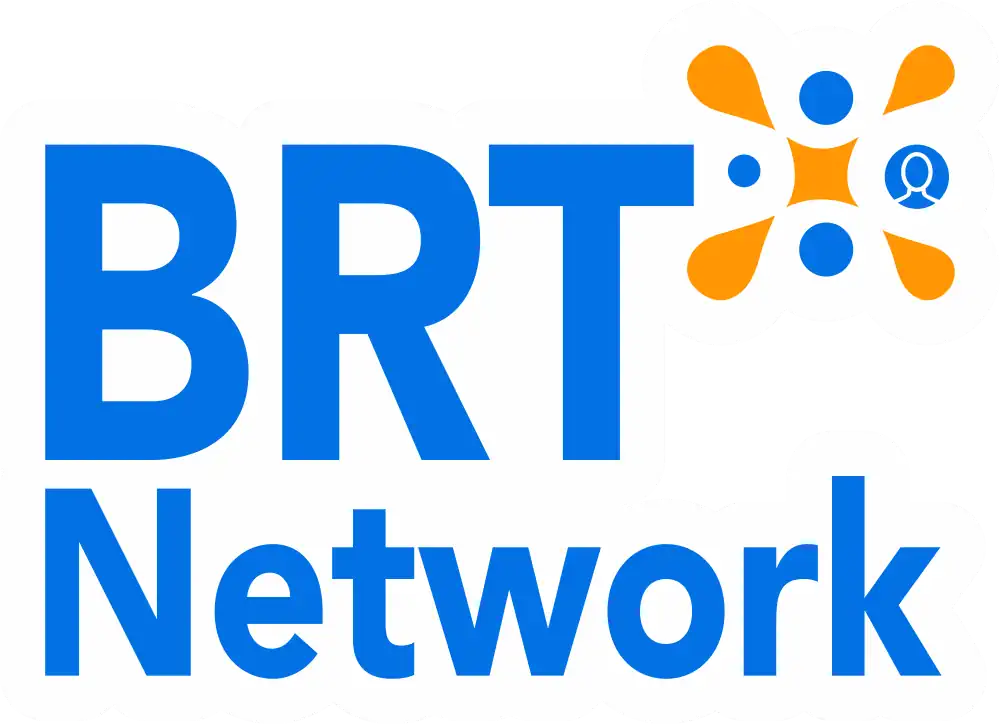Masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan sekitarnya. Mereka berasal dari berbagai ekosistem yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Mereka mengenal cara-cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pengelolaan sumberdaya alam masyarakat Gayo (Aceh) di Lokop, Talang Mamak pada masyarakat Riau, Sasi pada masyarakat Maluku, dan lain-lain (Primack, et al, 1998:297).
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam bersifat langsung dan tak langsung. Bentuk partisipasi masyarakat secara langsung yaitu upaya pencadangan suatu kawasan agar terbebas dari aktivitas manusia, seperti larangan aktivitas penduduk di area yang dianggap keramat dan suci di Gunung Butak, dan di gunung tersebut terdapat mata air untuk pemenuhan kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat secara tidak
Wilayah Pesisir
A. Definisi Pesisir Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara darat dan laut sehingga secara fisik terdiri atas darat dan laut. Bagian darat di wilayah pesisir yaitu bagian darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat air laut, seperti pengaruh pasang surut, ombak, angin laut, dan perembesan air laut. Bagian laut mencakup bagian perairan yang masih dipengaruhi oleh proses alami di darat, seperti aliran air tawar dan sedimentasi dari daratan. Penggunaan tanah di wilayah pesisir mengalami gradasi perubahan yang tajam bila dibandingkan dengan wilayah daratan dan laut (Sadyohutomo, 2006:61-62). Wilayah pesisir
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pada tahun 2000, United Nations mengadopsi MDGs (Millennium Development Goals yang dihasilkan pada konferensi internasional sekitar tahun 1990-an) yang dianggap cukup mendefinisikan tujuan global. Dalam hal ini, hasil dari pencapaian tujuan dianggap lebih penting dibanding bagaimana proses pencapaiannya. MDGs tersebut meliputi: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik; 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Mengurangi kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan kelahiran; 6. Melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7. Memastikan keberlanjutan lingkungan; 8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan. Dalam mendefinisikan pembangunan atau
Teori Lokasi Isard
Menurut Djojodipuro (1992:107), dalam pengembangan teori lokasi, Isard menggunakan peralatan ekonomi seperti kurva isokuan, garis perbandingan harga dan kurva biaya. Analisa keseimbangan lokasi industri Isard memiliki dua asumsi yaitu pertama adalah bahwa aktivitas produksi industri yang bersangkutan tidak mempengaruhi variabel lokasi, seperti harga satuan angkutan, harga bahan mentah, penyebaran konsumen dan penghematan ekstern yang dibawakan oleh gejala aglomerasi; sedangkan asumsi kedua adalah bahwa tingkah laku industri yang bersangkutan tidak mengundang balasan dari pihak saingannya. Lokasi industri yang bersifat immobile tentu akan berlokasi yang dekat dengan bahan mentah, sedangkan
Teori Lokasi Hoover
Pada teori sebelumnya yaitu teori lokasi Palander belum mencakup segi entry dan diminishing returns. Segi tersebut mendapat perhatian oleh Edgar Hoover, dimana teorinya masih banyak dipengaruhi oleh teori Palander. Berdasarkan atas asumsi persaingan bebas dan mobilitas tenaga, Hoover berpendapat bahwa lokasi industri ditentukan oleh biaya angkutan dan biaya produksi. Misalnya pada industri pertambangan batu bara akan berlokasi di area yang memiliki bahan tambang. Akan tetapi, perlu dilihat sampai sejauh mana pasar yang akan dijangkau. Jangkauan ini ditentukan oleh tinggi harga yang diminta oleh si pengusaha dan dibayar oleh
PENERAPAN TEORI LOKASI VON THUNEN PADA KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR – MALAYSIA (Studi Kasus: Perbatasan Sebatik – Tawau)
Gambaran Umum Pulau Sebatik Pulau ini terletak di bagian utara Kalimantan Timur yang dimiliki oleh dua negara, sebelah utara dan barat pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia dimana dibagi menjadi Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat dengan total luas 246,61 km2. Letak geografis tersebut merupakan potensi besar bagi daerah ini untuk mengembangkan jalinan hubungan internasional dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga mampu memcerminkan kemajuan pembangunan di wilayah Republik Indonesia.
Kawasan perbatasan Kalimantan memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap kota-kota di Malaysia seperti Kota Tawau, sedangkan aksesibilitas antar kota-kota